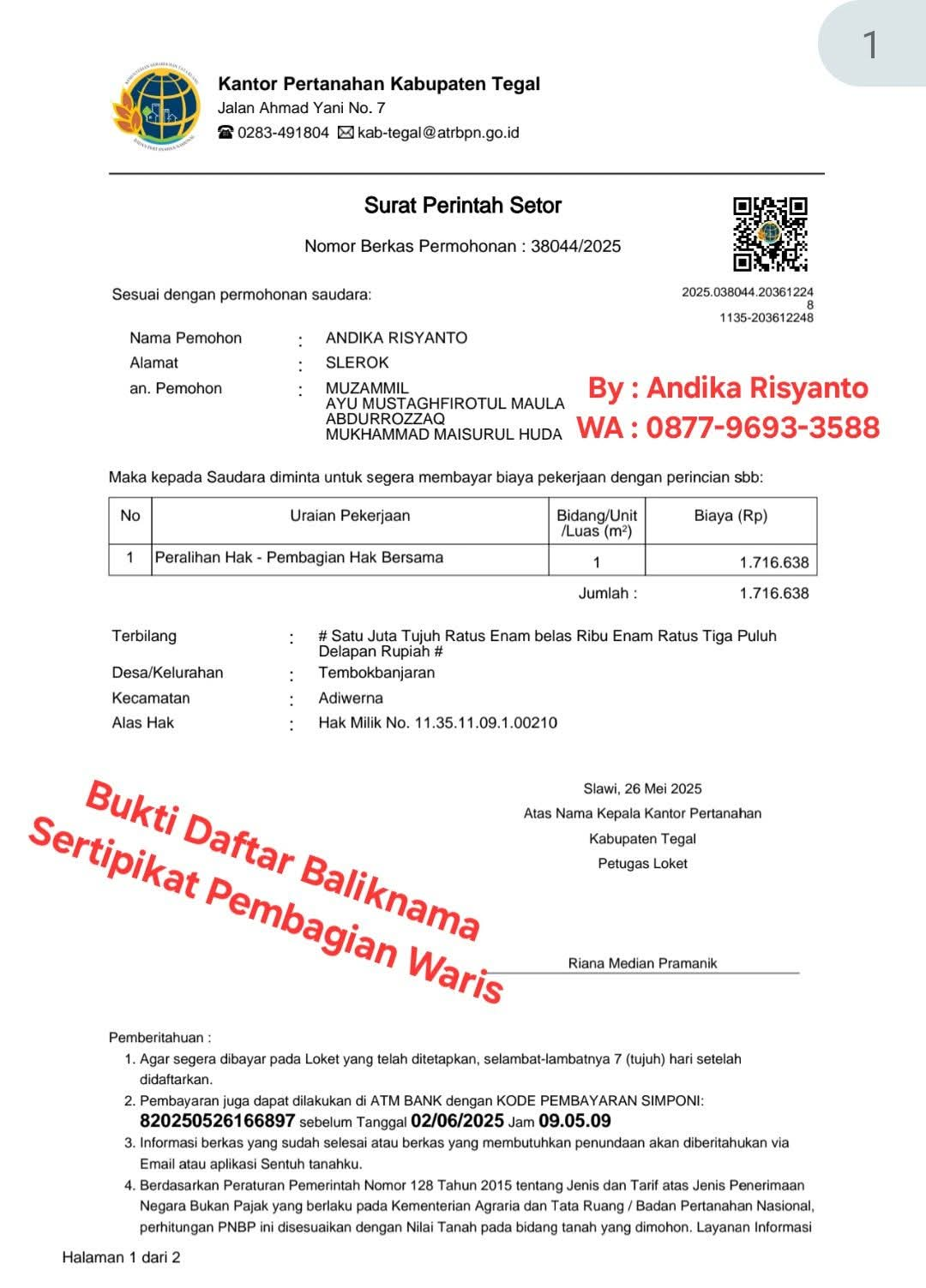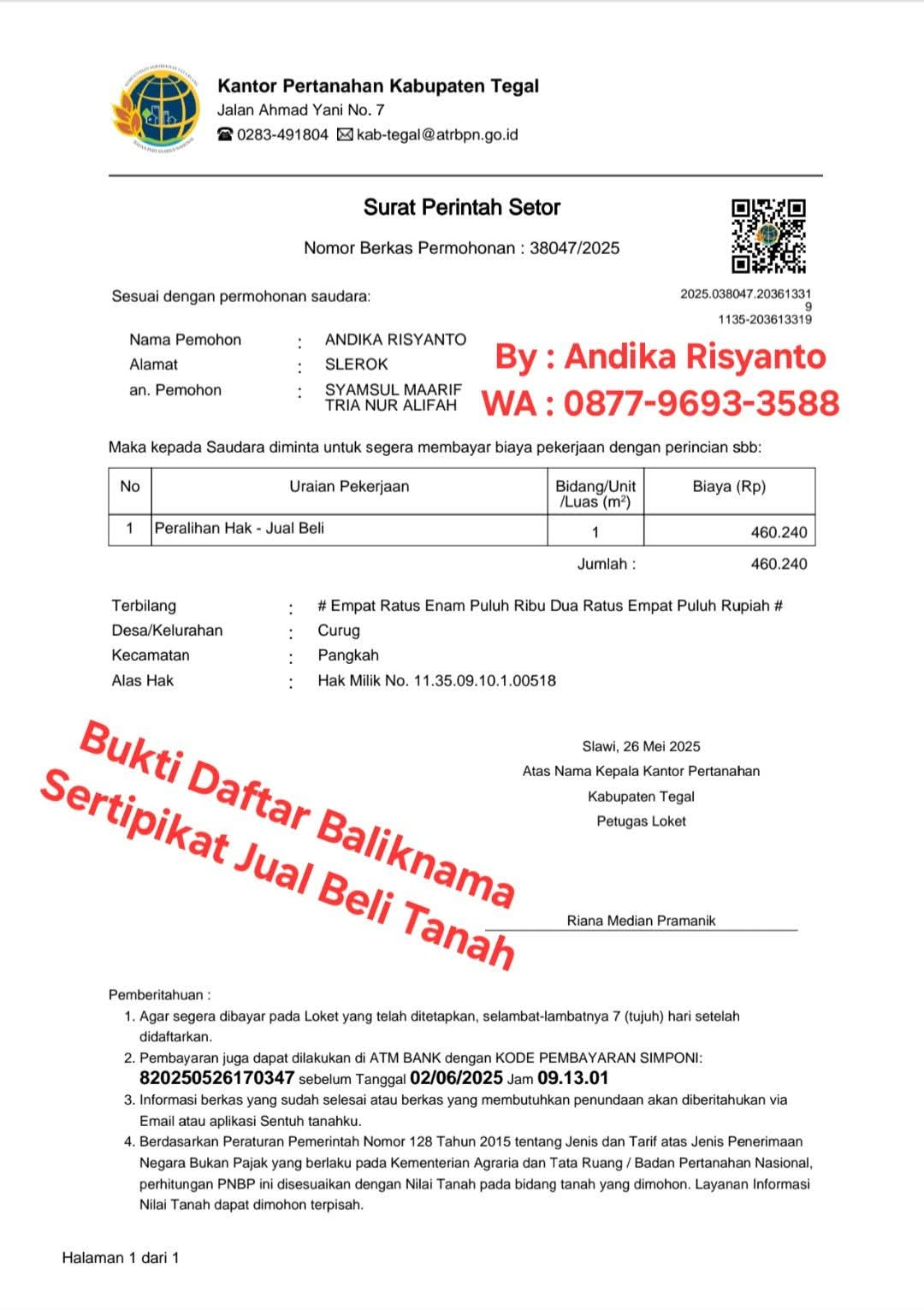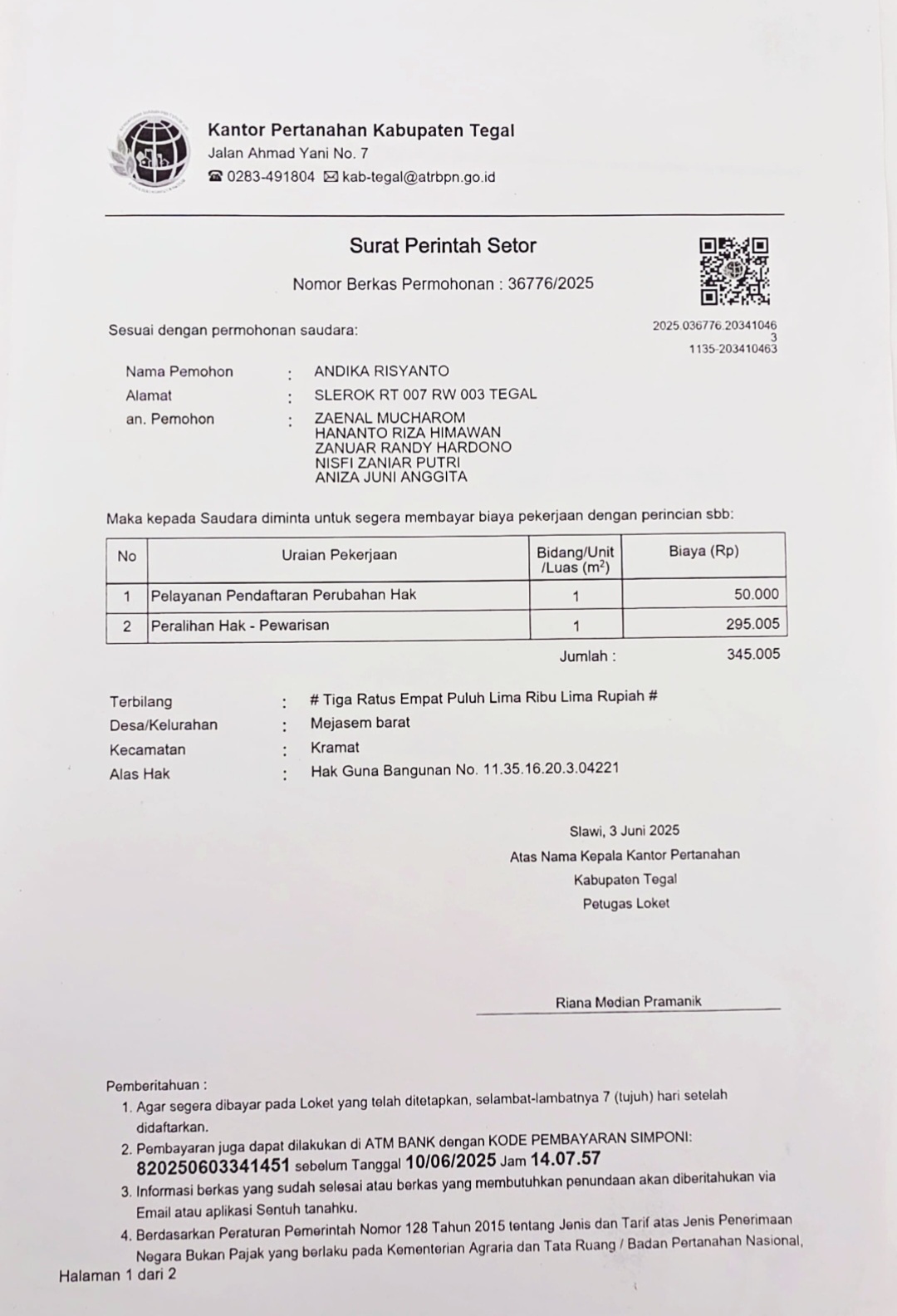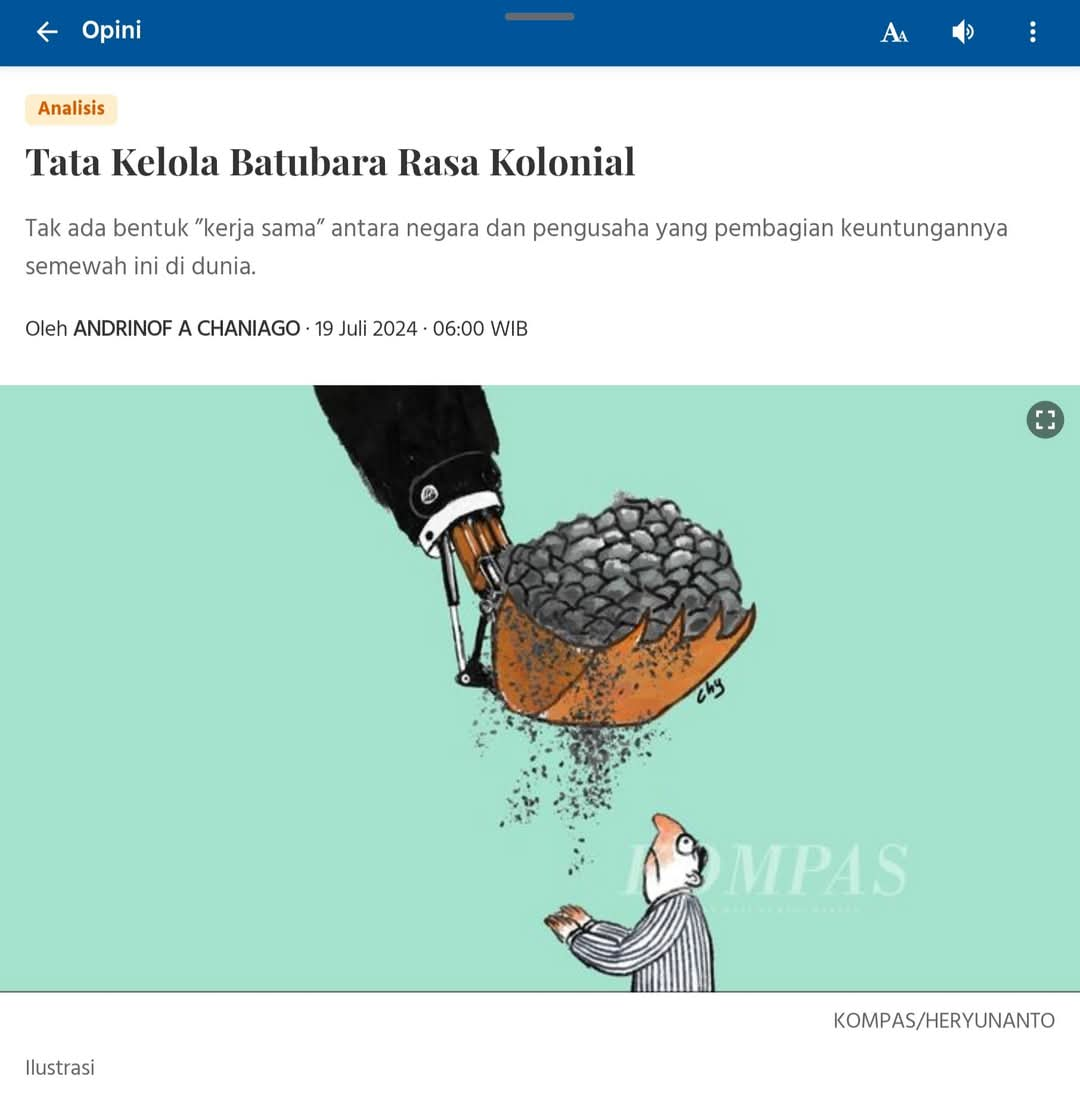
Tak ada bentuk "kerja sama" antara negara dan pengusaha yang pembagian keuntungannya semewah ini di dunia.
Opini Kompas, 19 Juli 2024
Oleh : Andrinof A Chaniago, Dosen Ekonomi-Politik di FISIP UI
Istilah kontroversial sepertinya terlalu lunak untuk kebijakan pemerintah tentang izin usaha tambang batubara untuk ormas keagamaan yang diumumkan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Pembenaran apa pun yang digunakan untuk kebijakan ini, baik tafsir fikih maupun kontekstualisasi ideologi, tidak punya kekuatan moral dibandingkan keburukan ganda dalam tata kelola tambang batubara saat ini.
Keburukan pertama adalah melanjutkan praktik eksploitasi masif batubara sebagai satu dari segelintir cadangan sumber daya alam yang tersisa di negeri ini. Kedua, mengukuhkan sistem bagi hasil yang sebagian besar hasilnya untuk membuat kaya raya segelintir pihak. Belum lagi kita bicara dampak buruknya bagi sistem politik, yang juga nyata.
Tulisan ini akan bicara tentang tiga keburukan tersebut sebagai bahan refleksi terhadap cara kita bernegara.
Paradoks kebijakan negara tentu berawal dan bertahan karena sikap paradoks orang-orang yang menjadi penyelenggara negara, baik perumus undang-undang di legislatif, maupun pelaksana jalannya pemerintahan di eksekutif. Untuk batubara, kita dengan mudah menemukan paradoks ini.
Misalnya, negara yang diwakili pemerintah dan didukung oleh legislatif, seolah-olah sangat serius ingin mengurangi emisi karbon lewat program transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan (EBT). Tetapi, di sisi lain, pemerintah dan para politisi juga pendukung status Indonesia sebagai negara pengekspor batubara nomor satu dunia.
Artinya, Indonesia yang seolah-olah serius ikut berperan mengurangi produksi emisi karbon, dalam kenyataannya melalui wilayah negara lain, menjadi penyumbang produksi emisi karbon dunia tersebut. Hal itu karena volume batubara Indonesia yang diekspor untuk dijadikan sumber energi dari bahan fosil, tiga kali lipat dari yang digunakan di dalam negeri Indonesia sendiri.
Sikap paradoks negara itu juga mengalir ke kebijakan fiskal dan kebijakan mengejar sumber investasi. Misalnya, untuk menjadikan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan sebagai kota bisnis, selain kota pemerintahan, pemerintah dan Otorita IKN sibuk berkeliling ke beberapa negara untuk mengundang investor, hanya untuk menghimpun dana selkitar Rp 100 triliun - Rp 150 triliun.
Dana itu dibutuhkan, jika pembangunan IKN hendak dipercepat, dari rencana jangka panjang yang sudah dirumuskan sebelumnya, yakni 20 tahun.
Padahal, jumlah Rp 100 triliun-Rp 50 triliun itu tak seberapa, jika dibandingkan dengan uang yang ada di kantong para pengusaha nasional dari hasil penjualan batubara mereka.
Sebut saja, Low Tuck Kwong, orang nomor satu terkaya di Indonesia dengan total kekayaan Rp. 435 triliun? Kita tahu, Kwong dan sejumlah pengusaha lain adalah penerima berkah lonjakan melambung tinggi harga batubara selama 2021 dan 2022.
ika dilihat dari bisnis intinya, sumber kekayaan yang membuat posisi Kwong melesat dari posisi nomor 30 ke nomor satu terkaya Indonesia adalah penguasaan pangsa produksi batubara yang besar, dengan produksi 35 juta-40 juta metrik ton (MT) per tahun selama 2021 dan 2022, serta lonjakan harga batubara di 2021 dan 2022 yang sempat mencapai puncaknya 400 dollar AS per MT.
Di luar Kwong dengan Bayan Resources-nya, masih ada satu perusahaan batubara yang volume produksinya dua kali lipat Bayan Resources, dan satu perusahaan yang volume produksinya satu setengah kali Bayan. Selain itu, ada beberapa perusahaan yang volume produksinya hampir sama dengan Bayan. Para pemilik dan pemegang saham perusahaan-perusahaan tambang batubara itu juga mengalami lonjakan kekayaan finansial yang fantastis.
Memberi perhatian pada wind fall profit usaha tambang batubara pada 2021 dan 2022 jelas jauh lebih bermanfaat daripada sekadar mengeksploitasi logika untuk membahas soal trade off antara lingkungan dan fungsi ekonomi komoditas tambang.
Dengan membedah distribusi keuntungan antara negara dan pengusaha dalam usaha tambang batubara, kita bisa melihat sebuah isu besar dalam bernegara. Gambaran ironis posisi negara yang amat rendah di hadapan pelaku bisnis akan muncul di sini.
Dari distribusi hasil tambang batubara dengan skema bagi hasil saat ini, kita akan melihat bahwa kebijakan negara, yang merupakan produk bersama pemerintah dan legislatif, bertentangan dengan semangat Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945. Pasal 33 Ayat 3 ini menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Jika melihat data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) batubara sejak gelombang eksploitasi batubara besar-besaran yang dimulai di periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), fakta ketidakadilan itu sangat jelas terlihat.
Begitu juga praktik ekonomi yang sangat eksploitatif. Tahun 2017 bisa dikatakan sebagai tahun dimulainya gelombang kedua lonjakan eksploitasi batubara, sepanjang Indonesia merdeka. Gelombang pertama lonjakan eksploitasi terjadi pada 2009, atau tahun terakhir periode pertama pemerintahan SBY.
Jika di masa Presiden SBY volume eksploitasi batubara melonjak dari di bawah 250 juta ton per tahun menjadi di atas 450 juta ton per tahun, di era Presiden Jokowi melonjak lagi dari di atas 450 juta ton per tahun menjadi di atas 750 juta ton per tahun.
Karena 80 persen dari produksi batubara nasional diekspor ke sejumlah negara yang masih menggunakan energi fosil, maka Indonesia pun tercatat sebagai negara pengekspor batubara terbesar di dunia selama 15 tahun terakhir. Ironinya, Indonesia tak termasuk ke dalam 10 negara dengan cadangan batubara terbesar di dunia.
Ironi berikutnya terjadi dalam bagi hasil antara negara dan pelaku usaha tambang. Terutama pada tahun-tahun windfall profit 2021, 2022 dan 2023, ketika lonjakan produksi juga dibarengi pula dengan lonjakan harga komoditas tersebut di pasar dunia.
PNPB batubara memang naik dari Rp 26,4 triliun pada 2020 menjadi Rp 58,7 triliun pada 2021, dan Rp 155,9 triliun pada 2022. Di luar PNBP, negara tentu menerima juga pajak perusahaan dan pajak lain dari perusahaan batubara.
Katakan, total penerimaan negara terkait produksi batubara mencapai Rp 300 triliun - Rp 400 triliun untuk total dua tahun itu. Angka ini seakan cukup berarti untuk penerimaan negara, padahal sebetulnya tak bisa dipandang menggembirakan. Sebab, dengan produksi rata-rata 610 juta ton/tahun dan sudah memperhitungkan harga untuk porsi domestic market obligation, nilai total hasil penjualan batubara selama dua tahun itu diperkirakan Rp 3.340 triliun.
Dengan biaya produksi maksimal 40 dollar AS per MT, total biaya untuk memproduksi sekitar 1,2 miliar ton batubara pada 2021 dan 2022 hanya sekitar Rp 780 triliun. Artinya, total keuntungan pelaku usaha setelah dikurangi biaya produksi sekitar Rp 2.500 triliun.
Jika dipotong lagi dengan beban royalti 13,5 persen dan pajak, hasil bersih yang tersebar ke para pengusaha batubara tak kurang dari Rp 1.500 triliun. Tak ada bentuk "kerja sama" antara negara dan pengusaha yang pembagian keuntungannya semewah ini di dunia. Ini juga sulit ditemukan di sektor lain.
SUMBER KETIDAKADILAN
Bentuk distribusi hasil produksi batubara yang penulis gambarkan di atas bukan saja memperlihatkan ketimpangan bagi hasil antara negara dan pengusaha, tetapi ia juga menjadi sumber ketimpangan politik. Bisa dikatakan, tata kelola tambang batubara sekarang ini tidak ada bedanya dengan tata kelola kayu hasil hutan alam dan tambang-tambang lain di era Orde Baru.
Bahkan, mungkin, tata kelola zaman Orde Baru lebih baik karena para pemegang izin penebangan kayu alam dan tambang itu tunduk pada kekuasaan negara. Para pengusaha tambang batubara era Reformasi bukan saja dengan mudah menjadi kaya raya, melainkan juga bisa membeli saham kekuasaan atau langsung ikut berkuasa di sistem demokrasi formal-prosedural yang ada.
Para politisi yang merangkap sebagai pengusaha tambang batubara punya keunggulan jauh lebih besar untuk mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan lkekuasaan di dalam lembaga negara maupun di pucuk pimpinan partai politik. Sementara pengusaha batubara yang bukan politisi, dengan sedikit sumbangan untuk para politisi yang sedang berkompetisi, sudah berpeluang melanjutkan usaha tambangnya dalam sistem pembagian yang tidak adil tadi.
Bisa dibayangkan, jika di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Timur para pengusaha tambang batubara lokal saja bisa menjadi aktor yang berpengaruh dalam pemilihan kepala daerah, bahkan pemilihan presiden dan pemilu legislatif nasional, bagaimana dengan pengusaha batubara kelas nasional?
Dengan sistem bagi hasil atas produksi batubara sekarang ini, sumber akumulasi kekayaan dan akumulasi kekuasaan para pengusaha dan politisi-pengusaha tentu akan terus membesar.
Dengan mempertahankan skema pembagian hasil antara negara dan pengusaha seperti saat ini, ketimpangan ekonomi dan politik di republik ini juga akan langgeng. Apalagi jika sistem ini diperkuat oleh ormas-ormas keagamaan yang mendukung kebijakan pemberian izin usaha tambang untuk mereka dalam skema bagi hasil yang sama.
Akan sedikit lebih adil jika ketika total laba bersih nasional dari produksi batubara dalam satu tahun adalah Rp 1.000 triliun, negara mendapat sekurang-kurangnya Rp 500 triliun. Jika total laba bersih Rp 1.500 triliun, negara mengambil hak sebesar Rp 750 triliun.
Dari skema seperti itu, bukan hanya ketahanan fiskal Indonesia jadi lebih kuat, tetapi sampai ke ketahanan ekonomi Indonesia juga bisa lebih baik.
Sebab, berdasarkan data indikatif arus masuk valuta asing ke dalam negeri selama dua tahun wind fall profit batubara, terindikasi uang hasil ekspor batubara itu oleh para pengusaha tersebut disimpan di luar negeri. Maka, sempurnalah penyimpangan dari Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 tadi. Lalu, di mana bedanya sistem eksploitasi kekayaan alam ini dengan zaman kolonial ?